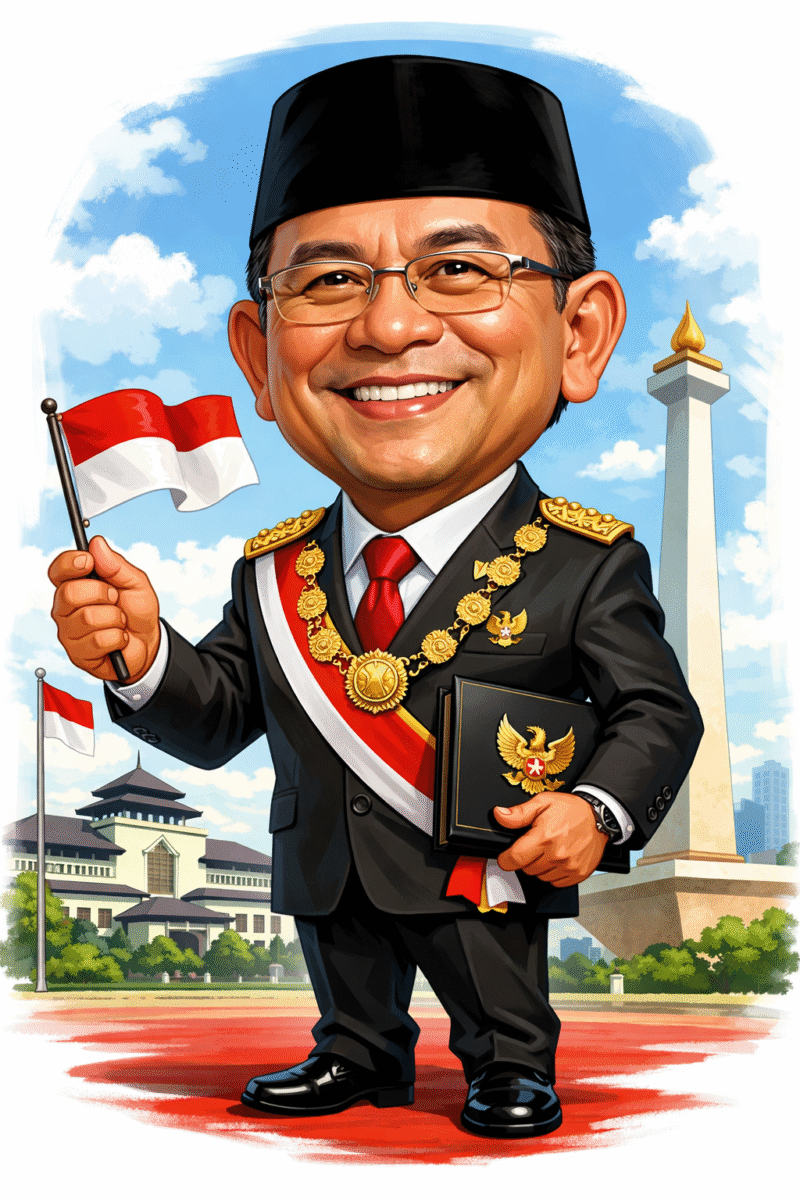Oleh: Chaidir Toweren
TribuneIndonesia.com — Saya membaca dengan saksama sebuah tulisan opini karya Bang Fauzan Azima yang dimuat di media online lintasgayo.co pada 1 Januari 2026, berjudul “Bupati Skin Care.” Tulisan itu disajikan dengan bahasa ringan dan satir, namun di balik kelugasannya tersimpan kritik sosial yang tajam dan relevan dengan realitas kepemimpinan daerah hari ini, terutama di wilayah yang kerap berhadapan dengan bencana.
Paragraf pembukaannya segera menggelitik sekaligus menggugah: “Di kampung kami, bupati bukan sekadar kepala daerah, ia adalah ikon perawatan diri.” Kalimat ini mungkin mengundang senyum, tetapi sesungguhnya menyentil nurani. Di tengah bencana hidrometeorologi ketika longsor merobohkan tebing, jalan hancur, dan akses hidup warga terputus sang pemimpin justru digambarkan tetap tampil rapi, bersih, dan nyaris tanpa cela. Dari situlah lahir julukan simbolik: Bupati Skin Care.
Julukan tersebut tentu bukan tanpa sebab. Dalam kondisi ketika jembatan putus, kampung-kampung terisolasi, dan warga harus berjuang sendiri untuk bertahan, kehadiran pemimpin semestinya menjadi sumber penguat harapan. Namun yang tampak justru sebaliknya: pemimpin hadir sebatas simbol, seolah bencana hanyalah latar visual, bukan tragedi kemanusiaan yang menuntut empati dan tindakan nyata.
Kontras itu terasa semakin kuat ketika dibandingkan dengan realitas di lapangan. Relawan datang dengan sepatu penuh lumpur, pakaian basah, dan mata merah karena kelelahan. Mereka bekerja tanpa sorotan, tanpa kepentingan citra. Dalam satire Bang Fauzan, sang pejabat justru digambarkan rajin beristirahat bukan soal tidur semata, melainkan sindiran tentang jarak emosional yang kian lebar antara penguasa dan rakyatnya.
Tulisan tersebut mendorong saya untuk merenung lebih jauh. Apakah fenomena ini hanya terjadi di satu daerah? Ataukah ini cerminan yang lebih luas dari gaya kepemimpinan lokal kita hari ini kepemimpinan yang lebih sibuk merawat citra dibanding merawat luka sosial?
Pertanyaan itu terasa relevan dengan realitas di daerah kami sendiri. Di tengah musibah yang melanda, beredar cerita tentang pemimpin daerah yang dikenal selalu tampil necis dalam berbagai agenda resmi. Penampilan, tentu saja, bukan sebuah kesalahan. Namun persoalan muncul ketika, menurut suara yang berkembang di masyarakat, sosok tersebut justru sulit dijumpai saat bencana benar-benar terjadi.
Ironisnya, pasca musibah, energi publik justru disibukkan dengan klarifikasi: di mana sang pemimpin berada, apa yang ia lakukan, dan mengapa publik dianggap salah paham. Di titik inilah problem kepemimpinan menjadi nyata. Dalam situasi darurat, rakyat tidak membutuhkan penjelasan panjang atau pembelaan diri. Yang mereka perlukan adalah kehadiran.
Kehadiran bukan sekadar datang untuk berfoto, bukan pula sekadar meninjau lokasi dengan pengawalan ketat dan waktu terbatas. Kehadiran adalah keberanian untuk berdiri di tengah lumpur, mendengar keluhan tanpa naskah, dan merasakan langsung denyut kesulitan warganya. Kehadiran adalah kesediaan untuk tidak risih dengan baju kotor, sepatu basah, dan wajah lelah.
Bencana adalah ujian paling jujur bagi kepemimpinan. Dalam kondisi normal, citra bisa dibangun melalui baliho, pidato, dan unggahan media sosial. Namun ketika bencana datang, seluruh lapisan kepura-puraan runtuh dengan sendirinya. Rakyat dengan mudah membedakan mana pemimpin yang benar-benar hadir, dan mana yang sekadar hadir dalam narasi.
Melalui satire “Bupati Skin Care,” Bang Fauzan sejatinya mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan soal penampilan, melainkan keberpihakan.
Bukan tentang seberapa rapi pakaian seorang pejabat, tetapi seberapa dekat ia dengan penderitaan rakyatnya. Pemimpin tidak dituntut untuk tampil sempurna, melainkan dituntut untuk tidak absen saat rakyat berada dalam kondisi paling rapuh.
Di daerah rawan bencana seperti Aceh, pejabat yang terlalu sibuk menjaga citra akan selalu tertinggal dari derita warganya. Rakyat mungkin lupa warna jas atau merek sepatu pemimpinnya, tetapi mereka akan selalu mengingat siapa yang datang saat jalan terputus, siapa yang bertahan di tengah hujan, dan siapa yang bersedia mendengar ketika suara mereka nyaris tenggelam oleh bencana.
Pada akhirnya, sejarah jauh lebih jujur daripada konferensi pers. Sejarah akan mencatat siapa yang memilih turun ke lumpur bersama rakyat, dan siapa yang memilih bertahan di tempat aman demi menjaga penampilan. Dalam konteks itulah, “Bupati Skin Care” bukan sekadar satire, melainkan sebuah peringatan: bahwa kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan jarak, dan kepemimpinan tanpa kehadiran akan selalu berakhir sebagai simbol kosong.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka di benak saya dan mungkin juga di benak banyak warga adalah: apakah pemimpin didaerah kami termasuk dalam satire yang disampaikan Bang Fauzan Azima?
Pertanyaan ini tentu tidak dimaksudkan sebagai tudingan, apalagi vonis. Ia lebih merupakan ruang refleksi bersama. Satire bekerja bukan untuk menunjuk satu nama, melainkan untuk menghadirkan cermin. Dan di depan cermin itu, setiap pemimpin berhak dan seharusnya melihat dirinya sendiri dengan jujur.
Jika publik sampai bertanya demikian, sesungguhnya itu bukan sepenuhnya kesalahan publik. Bisa jadi ada ruang komunikasi dan kehadiran yang terasa belum cukup terisi. Dalam situasi bencana, keheningan seorang pemimpin sering kali lebih gaduh daripada kritik paling keras. Maka wajar bila masyarakat mencoba membaca tanda-tanda, menafsir sikap, dan menghubungkannya dengan satire yang beredar.
Satire Bang Fauzan menjadi relevan justru karena ia membuka ruang tafsir itu. Ia tidak menyebut nama, tidak menunjuk daerah secara spesifik, tetapi membiarkan publik menilai berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Di situlah kekuatan kritik yang elegan: ia tidak memaksa kesimpulan, tetapi mengajak berpikir. Apakah seorang pemimpin sudah cukup hadir? Apakah empati sudah terasa, bukan hanya terdengar?
Pertanyaan “apakah pemimpin kami termasuk” sejatinya adalah undangan moral, bukan serangan personal.
Undangan agar setiap pemimpin daerah di manapun, menjadikan bencana sebagai momentum introspeksi. Bukan untuk membela diri, tetapi untuk memperbaiki jarak. Karena dalam kepemimpinan, yang paling berbahaya bukanlah kritik, melainkan ketika rakyat berhenti bertanya dan berhenti berharap.